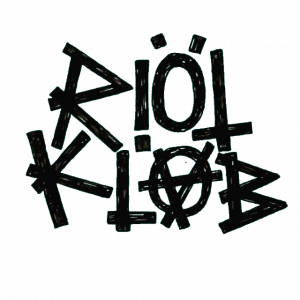Mijan meneguk lagi tuak itu, rasanya seperti campuran antara pahit;asam;manis; dan baunya yang sama seperti comberan. Warnanya yang seputih susu sangat menggiurkan, apalagi jika disandingkan dengan tambul rica nyambek(biawak). Diselingi ketawa cekakan bersama kawan-kawannya membicaran masa-masa sekolah mereka dulu di bangku SLTA, dan mengingat-ngingat Linda gadis populer di sekolah yang sekarang sudah menikah dan tampilannya berubah tujuh puluh derajat dengan kulit yang menggelap dan ukuran tubuhnya yang melebar. Lalu bahasan adu nasib antara mereka yang sudah menikah dan sekarang masih membujang.
Bahasan bisa liar ke mana-mana sampai ke perihal agama sambil mulut menguarkan aroma tuak yang khas.
Mijan selalu tidak banyak berkomentar untuk reuni orang-orang gila macam mereka. Dia selalu menyengir tiap candaan yang dikeluarkan.
“Aku kemarin di-inbox sama Eva, katanya sekarang menjanda. Terus curhat nyesal nyiain cinta saya cuma karena alasan pekerjaan saya jadi kuli batu,” ucap Afif sambil tertawa,”ternyata karma itu memang ada ya?” Lalu dilanjut menenggak tuak yang berada di gelas bambu yang orang lokal namai ‘centak’.
“Iya memang ada. Orang kemarin ada orang seberang tetanggaan sawah dengan saya. Dia suka nambah galeng. Saya biarin aja karena gak mau cari masalah, eh kemaren mati karena dipatok ular waktu ngarit.” Ucap Dikin menimpali.
“Mungkin sudah nasibnya aja itu.” Kata Topan berusaha logis, mengingat dia adalah PNS dan orang berpendidikan.
“Gak asik kamu pan, selalu merusak kesenangan.” Ucap Afif kesal.
“Daripada diam kayak Mijan.” Timpal Topan.
“Iyanih, kamu selalu diam.” Afif lagi.
“Ngantuk aku, puter musik Adella makanya, jangan Jambrud ae.”
“Oh iya, mak…. Ganti kaset Adella.” Teriak Topan kepada Emak pemilik kedai.
“Nah gitu dong.” Kata Afif sambil menghidupkan rokok kreteknya.
“Jadi kemaren kamu merantau ke mana Jan kog baru balik ke Tuban. Medsos-mu juga gak ada yang aktif, udah kayak orang hilang aja.” Tanya Topan penasaran.
Sambil memilin-milin batang rokoknya. Mijan teringat akan bayang-bayang ketika dia masih remaja dan memilih meninggalkan Tuban untuk merantau. Tentang hobinya bermusik hingga masuk sebuah kolektif punk di kota Surabaya, lalu berkawan dengan beberapa aktivis mahasiswa dan matanya terbuka akan ketimpangan sosial yang terjadi. Dia mulai banyak melahap buku dan berdiskusi setiap malamnya disela kesibukannya menjadi pekerja di kedai kopi milik kawannya yang sekaligus ruang pameran dan acara gigs musik.
Hidupnya sangat berapi-api, setiap berjalan ke manapun dia selalu marah. Dan kata yang selalu dia ucap adalah “anjing kapitalis”. Dia juga kadang menginap di sekretariat sebuah organisasi pers mahasiswa dan belajar jurnalistik di dalamnya. Dari sana dia punya bekal tentang jurnalisme dan menambah kegiatan dengan mewawancarai beberapa band lalu hasil tulisannya dicetak menjadi sebuh majalah fanzine.
Jika ada konflik yang terjadi di beberapa daerah, dia turun ke sana untuk menyumbang energi. Meski dia tau ketrampilannya terbatas, Mijan bisa menjadi suport system untuk warga yang bertahan melawan para pengusaha atau pemerintah yang ingin mencaplok tanah milik warga. Dia bangun pagi-pagi bersama tuan rumah tempat dia menginap dan membantu bertani atau sekedar menebas rumput. Dari situ dia belajar bagaimana bertani dan merawat tanaman.
Hidup Mijan penuh dengan semangat promothean, hingga pada suatu saat dia tergila-gila dengan seorang aktivis mahasiswa perempuan yang dia kenal pada acara konsolidasi aksi demonstrasi.
Dia masih ingat dengan kaca mata itu; rambut kepang itu; kemeja itu; dan senyuman yang menampilkan lesung pipit itu.
Awalnya dia malu-malu untuk berkenalan, mengingat dia hanyalah sebuah sempalan dibalik hirarki tak kasap mata di dalam aktivisme itu sendiri. Hingga gadis itu yang menghampirinya sendiri karena merasa tidak nyaman karena terus dia lihat. Mijan belajar lagi tentang apa itu feminisme dan patriarki setelah dijelaskan oleh gadis itu. Hidupnya jadi lebih makin berwarna, kini dia bisa berdiskusi dalam tanda kutip diselingi bumbu kedekatan emosional, mereka berdiskusi di mana saja, di kedai kopi, di bawah pohon, di perpustakaan, dan di indekos dengan tubuh diguyur peluh usai bercinta.
“Asyuu…kamu tidur sama mahasiswi cuk?” Tanya Afif seolah tidak peecaya.
“Wah, pasti cewek kuliah pergaulannya lebih bebas. Iya kan pan?” Sambung Dikin.
“Ya nggak semua, apalagi saya waktu kuliah lurus-lurus aja, jadi gak aktif organisasi atau apapun itulah. Cuma bikin nambah beban sama gak lulus-lulus.” Sergah Topan sambil memberi aba ke pada Mak untuk menambah satu porsi rica nyambek yang mulai tandas.
“Iya, sampai sekarang belum bisa melupakan dia, sekarang anaknya sudah pulang kampung dan dinikahi tentara. Idealisme itu cuma seumur jagung, dan hanya ketika di lingkungan eksklusif seperti kampus. Setelahnya kembali kerealita.” Ucap Mijan.
“Wah, bahasamu duwur hahaha.” Timpal Afif yang sepertinya mulai tinggi.
“Mbuh, aku yang dulu kuliah aja kalah.” Sambung Topan.
“Ya, namanya belajar kan gak harus di sekolah, di mana saja bisa.” Mijan melakukan pembelaan.
“Oke-oke, setelah itu bagaimana kelanjutan ceritamu.” Topan masih penasaran.
Hari-hari perlahan berjalan dengan lambat. Mijan mulai bosan dengan ruang dan segala hal yang dia bangun sekarang. Dia mengalami kesuntukan usai sepeninggal Rahma, ya, namanya Rahma. Dia masih ingat dengan nama itu. Terinspirasi dari serial dokumenter sekelompok jurnalis yang merekam kondisi yang ada di Indonesia yang selalu dibalut cerita keindahan yang selalu diagungkan namun nyatanya palsu. Dikuras semua tabungannya selama ini untuk modal awal touringnya berkeliling Indonesia menggunakan vespa kesayangannya dan melanjutkan apa saja yang masih bolong dari investigasi di dokumenter itu, selain dia hanya sendirian dan tanpa modal dari pihak manapun.
Lambaian tangan dari kawan-kawan kolektif memberi spirit tersendiri untuknya melakukan perjalanan ini. Di sela hujan dan panas, bertemu kawan baru dan mencicipi setiap teguk alkohol lokal dari tempat dia singgahi menjadi kesan tersendiri. Segala hal yang ada di jalanan dan apa yang dia lihat dia catat betul-betul dalam buku catatan usang miliknya yang kondisinya sudah memprihatinkan. Dekil, sobek, tinta yang meluber, bolong tersundut puntung rokok, dan lepek karena ketempuhan kopi. Beruntung tulisannya yang seperti cakar ayam masih bisa terbaca.
Dia benar-benar merasa tinggal diantara surga dan neraka. Terkadang dia bersyukur tinggal di bumi pertiwi ini, namun kadang dia marah melihat bagaimana orang-orang rakus merusak alamnya yang sudah seharusnya dijaga kelestariannya.
Hal yang paling menyobek hatinya adalah ketika dia sampai di Papua. Bagaiaman sehari kesampaiannya di sana, baru saja terjadi demonstrasi besar-besaran oleh warga asli. Warga sipil yang berdemonstrasi dihadang oleh aparat lalu diberondong dengan timah panas. Itu yang dia dengar dari cerita pemilik warung uduk transmigran dari Jawa yang dia singgahi waktu makan siang. Belum cerita lain yang tidak akan cukup penulis tulis di sini.
Mijan paling suka ketika dia sudah sampai di Kalimantan. Ada nuansa tersendiri di sana. Di sanalah dia bertemu dan jatuh cinta lagi dengan seorang gadis lokal di sana. Dia tinggal berbulan-bulan dengan warga yang sedang berkonflik dengan sebuah korporasi karena wilayah adat sukunya diekspansi oleh perusahaan sawit. Pada saat Mijan sibuk dari kebun usai membantu bapak tirinya di sana, gadis itu selalu berbasa-basi untuk sekadar bertanya, “Dari mana?” Atau, “Abang sudah makan?”. Dia juga yang merawatnya ketika sakit karena malaria sedang bapak dan ibu tirinya sedang berada di luar desa untuk menjual rotan ke pasar.
Namun cinta itu dipendam adanya, mengingat masih ada tugas yang belum selesai. Jangan sampai hanya karena perempuan segala tujuan diawal menjadi buyar. Mengingat cintanya yang lalu juga masih belum sembuh seutuhnya.
Tangisan gadis itu pecah mengiringi kepergiannya, namun perjalanan harus terus berlanjut.
Sesampainya di Sumatera, Mijan benar-benar minus, dia menjual vespa kesayangannya kepada seorang kenalan lama yang sedang berdomisili di Lampung. Lalu dia mulai melakukan estafet dengan menumpang truck yang selalu tak pasti tujuannya. Dia banyak mendapat cerita kehidupan supir truck yang liar, maskulin, nakal, dan segala resiko yang dihadapi.
“Aku punya istri dua, satu di Lubuklinggau, satunya lagi di Palembang,” Ucap supir, “masalahnya kalo jadi supir di Sumatera ini ya begal sama bajing loncat, makanya harus berkelompok sama truck lain, biar aman.” Tambahnya.
Tapi jika dipikir-pikir, pekerjaan apasih yang tidak beresiko? Semua kembali lagi, tergantung nasib dan meminimalisir kesialan. Lucu juga jika mengingat kriminalitas yang membahayakan nyawa tapi tidak ada tindakan yang tegas dari pihak berwenang. Lupakan saja, Mijan terlalu lelah jika mengingat itu dan itu lagi.
Perjalanan Mijan di Sumatera terbilang agak lambat, karena dia harus mendekam di penjara beberapa bulan karena menampar seorang preman yang memalak warung kopi yang dia singgahi. Dia naik pitam dia tantanglah preman itu. Terjadilah perkelahian “bak,buk,splash” si preman bonyok. Setelah itu dia bingung jika preman itu memanggil kawannya, akhirnya dia meminta si pemilik kedai untuk mengantarnya melaporkan diri ke Polsek terdekat.
Di penjara dia banyak tau bagaimana lingkungan di balik teralis besi. Di dalam sel hidup di lingkaran para napi dia banyak tau soal narkoba, senioritas, kesukuan, dan peraturan yang ketat di dalamnya. Selain dia juga mencoba memasang gundu di batangnya karena ikut-ikutan napi yang lain.
“Mau lihat punyaku?” Tanya Mijan kepada kawan-kawannya.
“Ya gak maulah!” Ucap Dikin geli.
“Tapi kalo buat pelaku pemerkosaan itu memang dihabisin ya, sama napi di sana?” Tanya Topan serius.
“Yo mestilah.” Potong Afif.
“Setauku sih iya, soalnya pada waktu itu ada yang melakukan pencabulan kepada keponakannya yang masih empat belas tahun, dan dia melakukan pencabulan sudah tujuh tahun lamanya hingga si keponakan hamil. Dihajar habis-habisan itu sama napi yang lain. Sudah bukan lagi manusia dia kalo di penjara.” Tambah Mijan.
Setelah menghirup udara bebas, Mijan melanjutkan perjalanan ke ujung Sumatera. Di sana dia mencoba apakah masih ada gerakan GAM di Aceh, ternyata masih ada namun mereka sudah renta-renta. Namun ingatan warga sipil pada saat Aceh dijadikan DOM masih menjadi cerita sendiri untuk mereka selain musibah tsunami. Dia iseng juga mengikuti petani ganja yang menanam ladang ganja di lereng-lereng gunung dengan medan yang sulit.
Dia juga mulai bekerja dengan orang-orang. Entah mencuci piring di warung untuk sekedar mendapat makan, atau memanen kopi dan menunggui durian di kebun. Upah yang lumayan untuk mebeli rokok dan makan di perjalanan. Dia juga banyak berjumpa perantauan Jawa lainnya–yang membawa sedikit emosional–karena sama-sama jauh dari kampung halaman.
“Wong Tuban to? Aku neng kene melu bedol desa trans mergo proyek Gajah Mungkur, rong lahir awakmu paling haha.” Ucap Ponaryo mbah-mbah yang kujumpai waktu istirahat di masjid dekat danau Singkarak yang indah dengan jalannya yang berkelok.
Namun raut wajah dan matanya nanar mengingat bagaimana kampung halaman dan pemakan leluhurnya sudah digenangi air menjadi saksi bisu kekuasaan Orba pada saat itu.
. . .
“Aduh wes mendem aku.” Kata Afif sambil menyederkan badannya di tembok warung.
“Hal semacam itu pasti menguras emosi ya?” Tanya Topan.
“Ya begitulah, namun ada kesan tersendiri dan dipelajari dari perjalan.” Ucap Mijan.
“Aku ke WC dulu.” Ucap Dikin sambil menghidupkan rokok Sukun dan berjalan sempoyongan. Ternyata dia bukan menuju toilet, tapi menuju semak-semak yang berada di dekat sendang.
“Awas, jangan nguyuh di sana, kesambet kamu nanti.” Kata Afif yang wajahnya memerah ketika sedang tinggi.
“Setelah itu kamu balik ke Tuban?” Tanya Topan.
“Ya belum, ke Jakarta, Bandung, lalu balik ke Surabaya dulu untuk acara syukuran karena kembalinya saya dan ketemu kawan-kawan.” Sambil mengingat-ngingat kejadian.
Setelah segala perjalanan itu Mijan pulan ke Tuban. Tidak banyak yang berubah dari kabupaten yang terletak di Pantura ini. Panas menyengat dan kondisi kering dari pemandangan pegunungan karst. Namun sudah mulai berdiri pabrik-pabrik di sekitarnya. Bukit-bukit kapur yang botak dan dari kejauhan terlihat seperti salju.
Kedatangannya disambut oleh kawan-kawannya dengan hangat, seperti saudara yang sudah lama tak kembali, seperti legenda yang selalu dibicarakan. Terutama tentang ketangguhannya menenggak berjerigen tuak tanpa mabuk. Dialah dewa mabuk yang telah lama hilang dan kembali lagi, namanya Mijan.
“Jadi bagaimana untuk catatanmu selama perjalanan itu?” Tanya Topan masih penasaran.
“Catatan itu hilang ketika aku sampai di Jogja. Kota itu menawarkan keramahan yang penuh dusta.” Kata Mijan dengan wajah datar.
“Lalu setelah itu?” Topan kurang puas.
“Seingatku, aku tidak pernah menaruh buku itu sembarangan dan selalu menaruhnya di dalam tas. Namun hal sial terjadi ketika aku menaruh di kontrakan milik kawan. Jadi kontrakan itu adalah sebuah kolektif juga, sama dengan tempatku di Surabaya,” Menenggak tuak yang disodorkan Afif dan menghidupkan rokok lagi, “karena banyak orang di sana dan keluar masuk secara bebas, kejadian yang tidak diinginkan mungkin terjadi.”
“Sayang sekali.”
“Bodohnya saya menyadari waktu di Semarang, lalu mencari informasi tentang buku catatan itu, namun tidak membuahkan hasil.” Tutup Mijan.
. . .
Setelah obrolan itu yang penuh busa tuak, beberapa bulannya terbit sebuah buku berjudul, “Tanah yang Tidak Lagi Suci”, menghentakkan kesusteraan Indonesia. Karena tulisannya yang tulus dan menguras emosi bagi para kritikus dan penikmat sastra. Sedangkan Mijan tewas karena bunuh diri. Dia meninggalkan secarik puisi, isinya begini:
Kita hanya merayakan kesenengan di atas puing-puing keruntuhan peradaban.
Tidak ada yang perlu disikapi secara berlebihan.
Manusia akan tunduk dan tersungkur pada garis takdirnya, namun tidak bagiku.
Inilah jalan yang kupilih
Tugasku sudah berakhir
Dan segalanya kembali menguap
Tidak ada yang perlu diker mati-matian.
◦