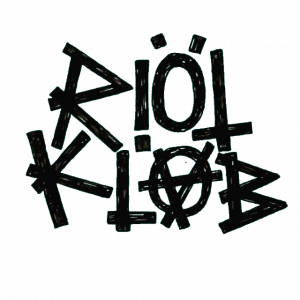Sampainya beberapa kilometer jalan utama di kota ini turut mencatat betapa besarnya saat itu aku benar-benar terhanyut ke dalam percakapan antara dua individu yang kehilangan arah pasca putus cinta. Kedai kopi pukul sembilan, Jalan Jenderal Soedirman, Halte Bus, dialog sederhana yang cukup menghangatkan ketika hujan tak turun dan menimbulkan sinis bapak tukang nasi goreng. Ah, kami juga enggan jika harus berciuman sambil memelihara Menara Teratai.
Aku adalah seorang penulis naskah sekaligus sutradara pementasan teater yang selalu gagal. Memalukan sekali jika aku harus mengakui bahwa aku benar-benar mencintai duniaku ini. Naskahku terlalu cetek untuk dibedah, apalagi keilmuanku tentang seni peran, sampah!
Bagiku sebuah pementasan adalah representasi dari kehidupan sehari-hari, dan terkadang menurutku ada banyak hal sepele yang masih luput dari jamahan anak-anak seni ini. Ya, bisa jadi memang isu tersebut tidak sebegitu penting untuk diulas, memangnya apa sih urgensinya? Tetapi bukankah sebuah keresahan dalam kehidupan sehari-hari tidak harus melulu tentang hal-hal yang besar? Sekali lagi salam seni untuk keberpihakan!
Pernahkah ada satu orang yang bertanya tentang “bagaimana bagaimana menjadi seorang aktor yang baik?” dan jujurakupun tidak tahu penjelasannya. Sebuah kritik untuk diriku sendiri yang hanya berangkat dari kenekatan dan pengalaman pribadi — aku adalah seorang fakir yang sama sekali tidak memiliki pegangan yang cukup tentang keilmuan pada seni peran — yang kutahu seorang aktor selain harus menguasai teori hal-hal yang bisa mereka pelajari da re buku , berani bertanya dan menelanjangi tokoh-tokoh yang sejalan, mereka juga harus punya bank emosi. Bank emosi ini biasa dijadikan sebuah acuan ketika dituntut untuk mengungkapkan suatu keadaan tertentu. Aku hobi menyimpan sebanyak-banyaknya memori dan perasaan ketika dibenturkan dengan segala macam kondisi.Bagiku, menjadi seorang aktor artinya memahami dirinya sendiri dan juga orang lain.
Kebetulan sekali saat itu lawan bicaraku adalah seorang mas-mas nyentrik tim artikel di teater kampusnya — aspek yang sama penting dan mendukung sebuah pementasan — dan kami memiliki satu keresahan yang sama tentang “bagaimana cara membuat pementasan (masing-masing dari kami) ini berhasil ? ” , sebut saja namanya Sueb.
Sepengalamanku pribadi, selama aku diasuh oleh ‘Kakak-kakak Senior’-ku, menjadi seorang sutradara yang artinya menjadi seorang ‘Ibu’, bukan secara harfiah, aku menerjemahkannya sebagai sebuah karakter yang menggambarkan sifat-sifat pengayom, sabar, dan tegas. Hal itu pula yang kudapatkan ketika mereka menjadi orang tua angkatku, bersama mereka aku menjelma seorang bayi yang harus disuapi, kembali belajar mengeja dan berhitung, membangun kedekatan sampai menyentuh ranah pribadi, mengikuti aturan-aturan di rumah baru, sampai akhirnya aku menyadari se boo pa seni dari semua hal yang kuanggap remeh saat itu.
Pernah pada satu waktu saya benar-benar muak dengan banyaknya tekanan. Hidup rasanya seperti terbelenggu di dalam jeruji besi, aku sulit beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang aneh ini, aku tidak bisa bebas. Rasanya ingin memberontak karena ini bukanlah diriku sendiri!
Wajar saja jika kecamuk itu ada. Senyatanya menjadi orang lain memang tidak mudah, hidup tujuh belas atau dua puluh tahun, lalu kamu terpaksa harus melahirkan dirimu kembali menjadi seseorang yang berbeda. Pun menjadi sutradara juga tidak mengulanginya, berkali-kali memutar otak untuk melakukan pendekatan secara pribadi dengan mengamati bagaimana cara aktor berpikir dan peka terhadap sebuah perasaan, sampai bisa masuk ke dalam dunia mereka lalu menciptakan dunia yang baru lagi.
“Kayanya di mata aktor-aktorku dulu, aku yang mereka kenal di luar bakalan beda sama aku ketika lagi latihan deh, aku cukup tegas”
“Aku kadang kasihan sama aktor kalau ditekan sama sutradaranya”
“Loh, kenapa? Semua keputusan pasti mempunyai konsekuensi, pun ketika mereka dengan sadar memutuskan untuk mengiyakan kesepakatan menjadi aktor.”
Lalu Sueb menceritakan pengalamannya, menata suatu tempat sederhana — bukan sebuah gedung mewah bertribun, bukan juga tertutup ruangan yang kedap suara — dengan benda-benda yang seadanya untuk dijadikan sebuah venue pertunjukkan, kami menyebutnya dengan meruang. Salah satu contoh konkritnya adalah ketika ia menikmati ke- chaos -an di tengah aksi massa.Persetan dengan orasi-orasi konyol dari para pemula kampus, lebih baik menyulang Whiskey sambil tertawa ria. Sebuah pementasan organik, benar-benar definisi dari “Aksi ini ditunggangi oleh kepentingan dan kepuasan pribadi salah satu golongan”.
Botol anggur yang menjadi katalis berhasil melarutkan kenyamanan malam, di saat itu pula kami tengah berperan dan meruang. Sueb bukanlah nama yang sebenarnya, hanya sebuah panggilan mesra saja, penokohan baru yang lain dari dirinya. Sama halnya dengan diriku, Nymphea dan beberapa karakter lain yang sengaja kubentuk sebagai pelarian dari badai dan kecamuk di dalam diriku sendiri.
“Jadi, kamu mau mengenalku sebagai pribadi yang mana?”
“Yang mana saja, menurutku semua sama”
Jemari kasar yang perlahan menyapu semut merah yang sedang berjalan-jalan dari leher hingga tiba di pipiku, sedangkan aku hanya bisa menatap penuh takjub tepat pada binar matanya.
Kami berangkat menuju latar tempat lain. Masjid Agung, bukan, Alun-alun. Jika boleh saya- review , fallitas umum ruang terbuka di sini cukup bisa menjadi alternatif bagi kaum muda-mudi miskin kota sepertiku yang masih bergejolak ingin menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekatnya. Kita bisa mengunjungi tempat ini pada pukul berapa, buka dua puluh empat jam setiap hari. Sembari melanjutkan dongengku pada bab selanjutnya, matakuliah lebih sering menampilkan rumputan di depan, terkadang juga sedikit melirik sekilas ke ujung sepatu. Berjalan sesampingan menuju sebuah kursi di pinggir taman, tepat di depan pohon Kembang Sepatu yang bermekaran.Merahnya menyala, merekah, seperti kilauan mentari yang menyusul beberapa saat setelah Adzan Subuh berkumandang. Di tempat itu kami kembali berteater ria, kami sedang membayangkan-pura — mencoba menampikkan rasa kesedihan dan kesedihan. Tapi entah kenapa sepiku sedikit teredam ketika kugapai sapa,
Sueb duduk di sebelah kananku. Berbeda dari yang sebelumnya, kali ini jarak kami tak sampai ada satu jengkal sepertinya, cukup intim untuk sebuah pembicaraan ngalor-ngidul ala orang yang seperempat kemabukan. Ia memandangiku lamat-lamat. Senyum sipuku mulai sedikit berkembang ketika mengingatnya. Kami membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi di ruang publik, dan di sekitar kami semakin ramai, sudah saatnya kami kembali beralih.
Untuk menuju ke parkiran kami harus melewati sebuah gedung pertunjukkan para badut-badut kesayangan warga kota yang terkadang muncul di portal berita, mereka gemar menggandeng isu-isu aneh. Badut yang haus akan validasi akan eksistensinya. Anehnya, masih ada yang percaya dengan kumpulan badut ini, lelucon yang sama sekali tidak lucu dan terkadang kurang tepat sasaran. Lebih baik aku melihat teman-temanku berpantomim di depan Gedung DPRD saat ada unjuk rasa daripada harus menikmati lawakan jayus dari mereka. Mungkin badut-badut plat merah itu ketagihan berlakon di bawah silaunya cahaya lampu sorot, menari di atas kanvas bermandikan warna, mengenakan topeng dan berperan setiap hari.Setiap lakunya dianggap penuh arti, setiap ucapannya selalu didengarkan dan diperhatikan oleh penonton. Selain itu, hidupnya juga sudah ditentukan oleh alur skenarionya aja, bergantung kepada sutradara. Kehidupan panggung yang terlihat sangat menyenangkan, sampai lupa turun panggung dan berbicara selayaknya manusia biasa.
Sudah saatnya pulang dan aku mengiyakan ajakan untuk melanjutkan percakapan dengan kami di tempatnya. Perjalanan dari sini menuju kota sebelah cukup memakan waktu, udara dingin menembus outer rajut, dan juga dress hitamku.
Pagi itu kami sarapan nasi uduk dengan sambal yang cukup pedas, makanan khas anak kost, harganya murah namun mengenyangkan. Setelah selesai sarapan aku lanjut mengirimkan tenggat waktu sambil misuh-misuh karena laptopku tak kunjung menyala. Saya menampilkan ekspresi panik dan cemas dalam satu kesempatan, untung saja rekan-rekanku cukup mengerti kalau laptop tua ini daripada butuh disayang sepertinya lebih ingin diganti. Boro-boro untuk membeli laptop, selama masa kemiskinanku ini terkadang aku lebih sering kembali mengencani buku-buku di atas lemari bajuku, meskipun keinginan untuk menghabisi mereka sudah tak kederas dulu, dan juga aku lebih banyak mengingat dan mengingat. Entah memikirkan apa, aku juga tidak tahu.
Di ruangan ini, selama dua hari kami sibukkan dengan diskusi kecil, menonton berita, dan juga melihat siaran langsung salah satu acara di kanal televisi yang memaksa kami membuang waktu beberapa menit hanya untuk mendengarkan lagu kebangsaan mereka. Karena kami adalah dua orang yang cukup nasionalis, maka kami memutuskan untuk bergumul dengan mesra dan ugal-ugalan ketika jamuan demi jamuan mulai mereka suguhkan. Memang sungguh baik negara ini selalu memberikan ruang dan kesempatan untuk bermesraan, bukan sebuah tindak mengungkapkan, ini adalah bukti kecintaan kami. Ruangan pribadi yang kami sulap menjadi arena pertunjukan baru; tanpa backdrop , properti, make up, musik bahkan naskah itu sendiri. Semuanya mengalir begitu saja, pertunjukan yang penuh dengan improvisasi. Kami tidak lagi peduli dengan apa yang sedang mereka lakukan dari dalam layar kaca, entah itu sebuah selebrasi selama tujuh puluh tahun kemerdekaan palsukah atau hanya ikut-ikutan saja. Tetapi, yang perlu digaris bawahi, adalah:
“Apakah masih ada panggung pementasan yang lebih apik dan backsound yang terdengar lebih romantis, dibandingkan dengan kasur ini dan lagu yang mereka nyanyikan tadi?”
Penulis: Zeilinaar