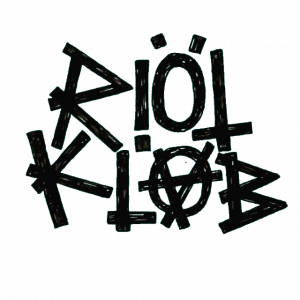Tanggapan kecil tentang absennya teori Sastra Anarkis di Indonesia

Menanggapi tanggapan Melati Mekar Arum tentang Teori Sastra Anarkis di Indonesia cenderung terlihat absen, barangkali memang benar, barangkali juga melenceng. Benar bila teoritisasi sastra, selalu memiliki sematan khusus kepada perguruan tinggi, kaum intelektual, dan otoritas lainnya. Teoritisasi tentu sangat membantu cara baca kita, atau dalam momen tertentu, ia akan mengekang aktivitas kesusastraan itu sendiri, sebagai ciri dari kehidupan seorang anarkis. Melenceng jika ternyata, sastra dalam definisi anarkis cenderung kaku, sehingga kita memerlukan kerangka sistematis untuk melihat sastra anarkis.
Dalam banyak ragam aktivitas kesusastraan anarkis, saya kira dua hal itu akan inheren dalam aktivitas, dan akan selalu menjadi gestur ganda. Pertama, dalam satu waktu, seorang Anarkis mungkin mencari lebih dalam apa arti sastra anarkis secara definitif, sehingga pencarian itu ia lakukan dalam bentuk sistematisasi pengetahuan dirinya. Kedua, dalam satu waktu pula, si pembaca, seringkali menginginkan dirinya keluar dari kerangkeng estetika yang ia baca dan pelajari, dan menciptakan karya yang baru – semangat berkarya. Dua hal ini bisa beriringan dalam satu waktu: kreator menentukan pijakan (teori) sekaligus berkarya untuk dirinya sendiri.
Dunia berjalan mandek, tetapi – saya tidak ingin menyematkan anarkis sebagai ideologi kaku, sehingga berisi fanatisme kepercayaan -isme sebagaimana jenis keyakinan lain di dunia ini – para pemercaya anarkisme selalu mencari bentuk baru, dalam jenis kesenian, baik melalui pola destruktif, dekonstruksi, dan atau bahkan konstruktif. Pemercaya ini, saya kira, bukan hanya berkutat dalam perdebatan ideologi sastra dan otoritas – seperti dewan kesenian misal – melainkan semangat kreatif yang dimilikinya, dalam suka maupun duka. Pemercaya ini, mulai dari dirinya sendiri sebagai individu – baik dalam sematan pemikir Stirner, atau Nietzsche – selalu berusaha menghancurkan, membentuk dan membangun ulang dimensi kreatif, minimal bagi dirinya sendiri, tidak untuk kebutuhan narsistik pengakuan dirinya sebagai “sastrawan”.
Masalahnya tentu akan beranjak pada estetika. Estetika apa yang menentukan, sehingga suatu karya disebut agung, atau lebih baik dari karya yang lain, itu soal lain. Seringkali, apa yang disebut “estetis” dalam satu ruang-lingkup waktu tertentu, berbeda cara resepsinya di ruang-lingkup yang lain. Sehingga perdebatan estetika, kendati Sejarah sering mencatat kanon, setidaknya akan mampir kepada relativisme keindahan karya. Sama seperti relativitas kebenaran yang manusa miliki itu sendiri. Dalam konteks estetika anrkisme, saya kira sudah banyak yang mengulas tentang ini, dan ada dua hal yang saya tangkap dari masalah ini: 1, Karya 2, beberapa karya yang saya suka.
Tentang Karya dan pertanyaan Isme
Untuk menggambarkan karya sastra, ataupun isme yang melingkupinya, saya kira ada kalimat baik yang mampu saya kutip dalam tulisan ini. Kalimat itu berasal dari Charlos Fuentes dalam esai, “Sepuluh perintah terhadap penulis muda”.
Sastra, pada akhirnya, memulihkan komunitas yang hilang; polis yang menuntut ujaran dan tindakan politik kita; civitas yang membutuhkan suara kita sebagai tindak peradaban agar kita mempelajari seni hidup bersama, lebih dekat, saling mencintai, saling mendukung satu sama lain kendati ada kekejian, intoleransi, dan pertumpahan darah yang tak pernah meninggalkan bayang-bayang pikiran manusia yang –terlepas dari semua itu—diterangi oleh cahaya keadilan.
Karya seni, atau khususnya sastra, tidak berlaku untuk kekuasaan. Sekalipun dalam beberapa konteks, sastra sering diciderai oleh ambisi kekuasaan. Bukan karena sastra itu suci, melainkan fungsi sastra itu sendiri, sebagaimana kaum anarkis percaya, ia harus memunculkan suara dari yang tak tersuarakan. Suara itu bisa dalam bentuk apa saja, mulai dari seorang nihilis, sampai seorang fasis sekalipun. Ada cerita menarik, bagi saya tentang kisah seorang Fasis dalam lanskap catatan Gabriel Garcia Marquez. Tentu anarkis, dalam bentuk pemahaman menolak diktat, dan percaya terhadap otonomi Individu. Gabo percaya ini, dengan demikian ia menulis cerita tentang Tumbangnya seorang diktator.
Fasis dalam Sejarah adalah benalu. Karena dalam cara berpikirnya, fasis percaya, bahwa dunia dari tangannya akan berubah menjadi cerah. Fasis mengidap penyakit messiah complex. Fasis menganggap dirinya seorang nabi yang turun ke bumi, lantas mendaku ajarannya mampu membawa manusia keluar dari lorong kehidupan. Tetapi Nabi dalam satu waktu, adalah manusia biasa. Mereka memiliki emosi sunyi, sebagaimana manusia lain memilikinya. Dalam Tumbangnya Seorang Diktator, Gabo melihat kepiawannya menggambarkan kelemahan seorang diktator sebagai tokoh representasi penguasa seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam catatan kisahnya, tersebut misalnya, seorang Jenderal Laut Karibia yang memerintah selama 100 tahun.
Obsesi jendral ini sangat aneh, sadis, ironi dan sekaligus tragis. Dalam salah satu adegan, Jenderal ini demi melihat nama besarnya, melakukan perayaan kematian palsu. Ia menunjuk salah seorang ajudannya, agar menyamar menjadi dirinya, lalu berakting mati di depan banyak khalayak. Kabar mulai tersuar, dan masyarakat mengira bahwa memang Jendral ini sudah mati. Sebagian besar masyarakat senang dan merayakan pesta atas kematian Jendral ini, sementara sebagian lain seolah berduka. Dari balik layar aktingnya, Jendral ini menyiapkan parade kematian yang jauh lebih besar. Mereka yang berpesta atas kematiannya, dibantai habis, sementara yang berduka diberikan penghargaan.
Kekejaman kekuasannya justru takluk setelah ia berhadapan dengan istrinya di atas ranjang dan tidak mampu melakukan senggama. Menghadapi aktivitas seks, Jenderal justru kecipirit di celana pendeknya. Meskipun dalam memegang senjata terasa Tangguh, tampaknya penulis menjatuhkan kebesaran ini hanya karena aktivitasnya di atas ranjang. Pembantai sadis yang kecipirit karena malu dengan aktivitas senggama. Bahkan dalam bagian akhir cerita, saat Sang Jenderal ingin menceritakan ibunya, sebagai kanon anak berbakti, ibunya justru menolak. Dengan sikap legawa seorang Ibu, ibunya berkata jika dia tahu putranya akan menjadi diktator, dia akan memaksa anaknya untuk belajar membaca.
Siapa sebetulnya Sang Jenderal dalam konteks kesusastraan? Apakah ia, memang dalam kata lain, betul-betul manusia “yang sadar”, atau ia hanya seorang militer bentukan Negara sebagai Killing Machine?. Ini sisi paradoks dari kehidupan yang tak tercatat Sejarah, karenanya Sastra, sebagaimana argumen Fuentes melihat yang paradoks sebagai dunia apa adanya, melawan dunia palsu yang diciptakan oleh otoritas Sejarah.
Dalam pemahaman anarkis, seberapa kuatnya isme dipijak, ia perlu diruntuhkan jika dalam prosesnya dengan cara-cara dogmatis. Secara tegas, misalnya Terapi Minor pernah menyampaikan dalam lirik “Caramu tak ubahnya Maois, yang mendoktrinisasi para sipil dengan bumbu struktural”. Dimensi kreatif ini yang tak dilihat Sejarah, saya kira, banyak para pembelajar paham anarkis mengerti, karya-karya yang mereka hasilkan sebagai individu menembus banyak batas Sejarah. Bahkan mereka, menembus batas aktivitas sastra kanon itu sendiri, seperti dalam esai Melati Mekar Arum berkata, “Cumbu Sigil adalah upaya lain, bahwa Sastra Indonesia tak hanya terbayang di balik punggung Chairil”.
Beberapa karya yang saya suka
Ada dua karya yang belakangan hari saya suka, setelah bercakap dengan salah seorang teman. Kedua karya itu dalam bentuk puisi, penulisnya, Melati Mekar Arum dan Melati Mekar Arum. Sebentar, saya menyematkan kedua puisi ini, jika memang kedua penulisnya meyakini mereka seorang Anarkis, atau setidaknya belajar tentang Anarkis meski hanya sekedar dalam cara pandang estetika. Jika penyematan “Anarkis” ini tidak tepat, saya tidak memaksa.
Puisi pertama dari Melati Mekar Arum. Saya tidak mengenalnya secara personal, selain mengenal karyanya melalui teman saya. Puisi ini, bagi saya, memiliki kekuatan naratif dan lepas dari bentuk konvensional. Saya tidak ingin mengulas satu per satu puisinya, tetapi saya akan mengambil lanskap general mengapa saya suka, dan mengapa karya ini bagus.
Pertama, tentang puitika tubuh. Melati Mekar Arum, saya tidak mengenal latar belakangnya, hanya saja melalui tulisannya, terasa ia menarasikan tubuh dalam bentuk puitik tanpa harus memaksa kita memahami tubuh orang lain. Sehingga membaca puisi Melati Mekar Arum, seolah membaca gerak tubuh yang meliuk dalam semesta Bahasa. Ada alasan logis, saya kira, sejauh pengamatan saya, tentang cara Melati Mekar Arum menggambar tubuh dalam puisi. Wacana tentang tubuh, yang ditawarkan oleh Melati Mekar Arum keluar dari Konvensi pemahaman “kebertubuhan” sebagaimana Alam Pikir Indonesia membaca tubuh. Dalam semesta Bahasa Indonesia, saya kira tubuh adalah penjara derita kehidupan. Sehingga Bahasa Indonesia, ataupun pengaruh adat di belakangnya, seringkali menggambarkan tubuh sebagai sesuatu yang purna, bukan sesuatu yang mengalami proses “kebertubuhan”. Sulit rasanya melakukan konveksi kebahasaan dari Bahasa Indonesia menuju Bahasa Tubuh dalam Puisi Melati Mekar Arum, karenanya logis bila bentuk yang ditawarkan Melati Mekar Arum cenderung lepas dari tradisi bentuk perpuisian Indonesia. Mari lihat secara seksama
rokok masih menempel/ di mulutnya yang mungil /satu gesekan korek / isap tembakau kretek / lepas tangan, satu ciuman / mendarat peluk hangat / di atas ranjang revolusi
suara rudal/ seperti trombone/ nyalakan lagu melodi / goyangan kita/ di part-party / di atas ranjang / revolusi telanjang / menanam benih / generasi yang melawan/ moral, tak berlaku / sebab lajang / disimpan di tweet / menanti fwb-fwb / gadis-gadis pinterest /dan fantasi-fantasi/ otak ngeres.
Metafor yang digunakan oleh Melati Mekar Arum, saya kira dalam beberapa hal, mampu menggambarkan semesta tubuh Perempuan dalam puisi. Gadis-gadis pinterest, misalnya, adalah metafor memiliki kekuatan, karena dunianya. Dunia digital, dan segala macam bentuk perdagangan tubuh sebagai komoditas digital, biasanya hanya memiliki tanggapan diktat moral, bukan masalah kebahasaan. Melati Mekar Arum, mampu menggambarkannya sebagai “dunia” yang perlu disuarakan keluar. Keluar dari konvensi Sejarah dan bentuk, barangkali. Atau metafor lain, seperti “fwb” “rudal seperti Trombone”.
Sementara dalam Puisi Bardjan, hampir serupa dengan Melati, hanya saja ia mencatat dunia domestik yang nasibnya serupa dalam kejadian pengalam kebertubuhan. Bardjan mampu merekam dunia domestik, dan memasukkannya dalam semesta puitika, dengan pertimbangan barangkali, sulit membahasakan problem domestik dalam konvensi bentuk sebelumnya, yang selalu terkungkung dalam lanskap “ruang domestik” dan alam pikir Indonesia. Bahkan Bardjan mampu menggambar tubuh sekaligus, dalam bentuk roman ruang domestik yang dinamis. Ruang yang tidak hanya berkutat pada seputar persoalan pembagian kerja antara suami-istri.
ari keseratus enam puluh delapan. fritz belum pulang
kios obat di seberang lamunan
memamerkan vialvial penenang. satu kuteguk
sebelum ia jadi kolesterol di tengkuk.
insomnia yang mencatat spandukspanduk politik.
esok adalah hari baik. tapi adakah masa depan
untuk kita? jika iya, apa warnanya?
asbak warung kopi mengoleksi memori
dari pertemuan kita terakhir–neon sign
menubruk mata yang sunyi. mudamuda berlari
dalam frame per second yang lamban. blur meleleh
pada mukamuka tampan. seperti film auteur hong kong
yang kutonton sekali sebulan.
jam dua kioskios tutup; mesinmesin karaoke
tak lagi bernyanyi lagu favorit kita.
taksitaksi menjemput impian masa muda
pulang ke rumah–masihkah ada rumah untuk kita?
jika iya, apa warnanya?
malam rabu sebelas derajat celsius
aku alergi dingin. sinus buruk mencocok pucuk mimpi.
gemetar dada menafsirkan benzodiazepine
jadi stasiun penghantar duka.
kueja seperti mereguk dokterdokter jiwa.
fritz fritz fritz
kembalilah fritz! f r i t z
kuarsipkan namamu
di dalam sini (menunjuk payudara)
a b a d i
Catatan dialog berbagi masalah perpuisian
–
Penulis: Aman a.k.a Bram