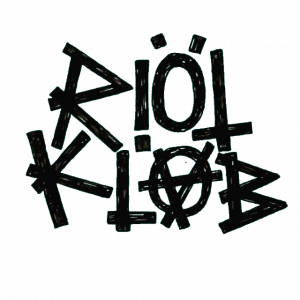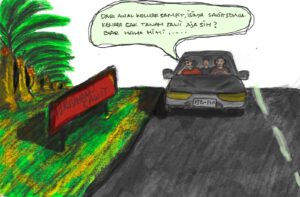
Terkadang saya ingin menjadi seorang backpacker, dan mendokumentasikan perjalanan saya dalam tulisan. Hal itu terbesit di pikiran saya setelah membaca karya-karya dari Agustinus Wibowo beberapa tahun yang lalu. Namun sialnya, tidak semua orang memiliki keberanian meninggalkan karir, meninggalkan tanggung jawab pada orang tua; lalu memilih mengangkat ransel untuk menjelajahi surga tersembunyi di seluruh penjuru dunia bermodalkan buku Lonely Planet.
Selain itu, saya juga banyak dipengaruhi buku-buku para petualang lainnya seperti Ring of Fire, catatan Walles, dan buku-buku antropologi seperti Graeber dan Benedict Anderson
. . .
Dari dulu memang sudah terbersit di pikiran saya untuk mengunjungi Kalimantan Barat, entah kapan, pasti itu akan terjadi di benak saya. Sampai ada satu kesempatan ketika ada kawan yang menawarkan untuk ikut dengannya ke Pontianak dalam rangka tugas kerja. Tentu saja ajakan itu kuiyakan dan tidak ingin menyia-nyiakannya.
Kalbar memiliki keunikan tersendiri menurut saya karena memiliki perbedaan kultur dengan provinsi yang pernah saya tinggali seperti Kalteng dan Kalsel, meski sepulau. Lalu segera saya hubungi kawan-kawan saya yang ada di Pontianak jika saya ada agenda ke sana.
Ini akan menjadi perjalanan yang melelahkan, menembus tiga provinsi dengan estimasi waktu 32 jam jika melihat google maps via darat. Persiapan kami tidak banyak, mobil hanya berisi tiga orang. Perjalanan tidak ada yang berarti ketika masih berada di wilayah Kalsel, untuk menuju Kalteng, tepatnya ke arah kota Palangkaraya. Pemandangan yang disajikan hanyalah jembatan, dan sungai-sungai kalimantan yang ukurannya lebar-lebar itu. Perjalanan agak melelahkan mungkin ketika masuk kabupaten Pulangpisau, karena kondisi jalanan yang makadam.
“Setidaknya, sore kita sudah sampai Sampit.” Kata kawanku, sambil memacu mobil dengan kondisi jalan yang minta ampun hancurnya, belum lagi masih ada proyek pelebaran jalan dan genangan akibat hujan.
Masuk wilayah Palangka, tepatnya Sebangau, terlihat jelas bagaimana kabut asap menghalangi jarak pandang, meski hujan sudah lumayan menetralkan kepekatannya. Musim kemarau yang panjang tahun ini benar-benar menjadi cobaan untuk masyarakat Kalteng, Karhutla semacam event tahunan untuk masyarakat di sana.
Setelah sampai di Palangkaraya, dengan bangunan dan patung-patungnya yang besar itu; kota yang indah dan rapi, namun terasa lengang–kami hanya menyempatkan untuk mengisi bahan bakar saja. Perjalanan dilanjut untuk tembak ke Sampit yang kira-kira estimasi waktu lima jam.
Keluar kota Palangka, pemandangan sudah mulai diisi dengan perkebunan karet dan sawit, beberapa pemukiman Dayak dengan ciri khas atapnya yang memiliki tanduk menyilang. Kawanku sibuk salip-salipan dengan beberapa kendaraan perusahaan dan travel, karena kondisi jalan yang lumayan lebar dan lurus tanpa tikungan yang berarti. Seingatku, mungkin ini yang dinamakan jalan Rusia, karena jalanan ini dulu pernah digarap oleh para insinyur Soviet untuk menjalankan proyek Soekarno dan berhenti pengerjaannya keti 65′ meletus.
Musik dangdut diputar, saya akhirnya tenggelam dalam lelap, hingga sampailah kami di kota Sampit. Mencoba menghubungi kawan untuk pesananku yang sudah lama belum kuambil, sembari menunggu di sebuah rumah makan murah di sana. Akhirnya dia datang dan menghentikanku dan kawan-kawan untuk melanjutkan perjalanan, untuk ngopi di kedai kawan lainnya. Sembari menunggu maghrib lalu baru melanjutkan perjalanan lagi.
Ya, seperti biasa, sesampainya di sana lebih banyak obrolan bagaimana kabar saya di Banjarbaru, lalu kegiatan apa yang kulakukan di sana, sambil dia menceritakan bagaimana perkembangan kegiatan anak muda di kota Sampit seperti dia mulai membuka Perpustakaan Jalanan dan meninggalkan graffiti untuk lebih fokus menggambar realis. Setelah menandaskan segelas kopi tubruk, dan adzan maghrib sudah berangsur tidak terdengar, kami melanjutkan lagi perjalanan ke arah Pangkalanbun. Melewati Tugu Perdamaian di pinggiran kota Sampit, sebuah simbol duka pasca tragedi dan sentimen ras yang sempat ramai di dasawarsa 2000-an. Sekarang Sampit tergolong semakin maju, tidak ada lagi gesekan antar suku dan semacamnya. Semua berjalanan beriringan demi kemajuan kabupaten Kotawaringin Timur.
Perjalanan menuju Pangkalanbun adalah perjalanan yang sangat melelahkan, banyak jalanan rusak, dan beberapa pembangunan dan perbaikan jalan. Sepertinya jalan adalah proyek abadi di provinsi ini. Kondisi jalanan yang gelap, kebun-kebun yang rapat, dan sedikit pemukiman. Kami masih berada di wilayah kabupaten Seruyan, tempat yang akan viral beberapa minggu lalu karena penembakan oleh aparat kepada warga yang menuntut haknya atas pembagian lahan plasma(dan memang sudah hak mereka). Sepanjang jalan melintasi bagian Barat Kalteng ini, saya akan menyaksikan sendiri bagaimana kedigdayaan sawit menggerogoti tiap inci lahan di sepanjang wilayah ini.
Memasuki kabupaten Kotawaringin Barat, yang masuk wilayah Pangkalanbun, jalan makin tak keruan rusaknya; memang benar ada yang mulus, tapi itu hanya beberapa kilo saja, sampai kita kalap dan baru menyadari di depan sudah ada lobak menunggu di depan siap untuk didamprat(orang sini menyebut kubangan dengan nama lobak). Aneh, mengingat gubernur Kalteng adalah orang Pangkalanbun, tapi jalan menuju rumahnya sendiri tidak diurus sama sekali. Apalagi jika sudah masuk kecamatan Pangkalan Banteng, jalan sudah seperti kubangan babi.
Kami sempat berhenti di sebuah SPBU, yang letaknya berada di persimpangan antara arah ke kota Pangkalanbun, dan Nangabulik kabupaten Lamandau. Berhenti sejenak melepas penat, mengisi bahan bakar, mencuci muka, dan menghisap rokok juga tentunya.
Perjalanan kami lanjut lagi, aku sudah tidak sabar untuk membuka bingkisan pesanan yang kuambil dari kawanku di Sampit. Segera kubakar dan kuputarkan kepada kawan-kawanku, sampai kami tenggelam dalam jalanan gelap yang disinari lampu mobil bak berputar-putar di dalam lorong gua. Mobil terus berjalan, kawanku di belakang sudah terkulai dan tertidur, sedang bodohnya kami memutar lagu The Paps yang semakin membuatku dan kawanku yang menyetir mobil tenggelam dalam pikiran masing-masing.
“Perlahan namun pasti.” Ucapku terkekeh, mengingat kami sudah mulai menaiki pegunungan dengan jalannya yang berkelok-kelok dan naik turun. Hingga sampailah kami di sebuah musholla, dan memilih untuk tidur di mobil saja. Mengingat masih ada hari esok dan ada nyawa yang perlu dipertahankan, meski tidak terlalu penting juga.
Paginya aku terbangun mendengar kawanku berbicara dengan seseorang. Dari obrolan itu kudengar bahwa mereka rombongan yang baru saja mengunjungi saudaranya di Muarateweh dan hendak balik lagi ke Pontianak. “Gila, itu perjalanan yang lebih menyakitkan lagi.” Dalam hatiku.
Kami menyiapkan diri, mencuci muka, sikat gigi, sembari menikmati sejuknya suasana pagi di Bumi Lamandau ini. Lalu perjalanan kami lanjut ke arah perbatasan provinsi, dengan estimasi waktu tiga jam. Sekaligus untuk istirahat dan sarapan.
Perjalanan mulai memualkan, kondisi perut kosong dengan konsisi jalan yang berkelok dan curam. Pemandangan pun tidak ada yang menarik. Apa yang menarik dari pegunungan yang gundul dan ditanami oleh sawit saja. Jika kalian melihat kasus penangkan Effendi Buhing karena mempertahankan tanah adat sukunya di Laman Kinipan, lalu muncul foto-foto kondisi hutan yang habis dan siap ditani oleh sawit; ya seperti itu yang kulihat. Saya bisa melihat juga sawit tingginya sudah seperti pohon kelapa, tidak masuk akal di logika saya, pohon ini bisa begitu superior di daerah ini.
Beberapa tempat masih ada hutan, namun itu tidak sebanding dengan luas perkebunan sawit. Beberapa Kebun-kebun karet milik warga yang mungkin sebentar lagi akan ditebang juga.
Sampailah kami di perbatasan, di sana ada rumah makan. Kami bisa makan dan mandi sepuasnya di sana. Meski terlihat dekat, ternyata sangat melelahkan melewati pegunungan di perbatasan ini(selain saya mulai sadar jika Kalteng benar-benar luas sekali). Usai menyelesaikan urusan perut, menyesap kopi susu panas, ritual mandi harus dilakukan. Mungkin disitulah aku bisa merasakan bagaimana segarnya air, yang sudah lama tidak kurasakan ketika menginjakkan kaki di tanah Borneo ini. Seakan membangkitkan kembali jiwa-jiwa yang mati, sendi-sendi yang hilang, akibat berada seharian full di dalam mobil.
…
Setelah masuk Kalbar, kondisi jalanan kurang lebih sama seperti di Lamandau, jalanan dipenuhi anjing rebahan dan mondar-mandir, bahkan ketika di Lamandau kami sempat menabrak seekor anjing, tapi kami tancap gas saja, daripada harus kena denda adat. Salah anjingnya sendiri tetiba nyelonong. Jadi saya lebih banyak tiduran, karena mual dengan kondisi jalan. Kawanku sibuk melihat para gadis-gadis lokal yang kami temui di jalanan, kasihan, diantara aku dan kawanku, hanya dia yang lahir dan besar di Kalsel dengan budaya konservatifnya itu. Jadi wajar dia sedikit shock culture ketika melihat wanita dengan pakaian terbuka sedikit.
Mungkin yang menarik menurutku adalah Tayan Hilir, itu sebuah pulau berpenduduk yang berada di tengah-tengah sungai. Lebih indah lagi karena ada jembatan panjang yang menghubungkannya.
Senja menyambut kami ketika hendak memasuki kota Pontianak, tepatnya di desa Ambawang. Desa yang indah dan terkenal dengan sentra pengolahan araknya. Sayangnya saya melewati desa ini pada saat musim kemarau, jika musim hujan, desa di sepanjang jalannya digenangi air dan terlihat seperti kampung terapung. Ketika kami pulang, kami sempat singgah sebentar untuk membeli sepuluh liter arak yang akan kami jadikan oleh-oleh kepada kawan-kawan di BJB.
Adalah kesalahan ketika masuk kota Pontianak pada saat maghrib, karena jalanan macet saat aktifitas pulang kerja dan hanya dua jembatan penghubung untuk menuju kota. Mungkin sekitar jam delapan baru bisa masuk kota, sembari makan malam di sebuah warung lalapan Lamongan. Lalu merebahkan di sebuah penginapan esek-esek yang dipesan temanku.
Sambil meluruskan badan dan menyegarkan diri dengan mandi, kami membakar lagi sisa lintingan terakhir. Lalu kawanku Gita dan Chowny menjemputku untuk mengajak ngopi, sedang dua kawanku tidak ikut dan memilih istirahat.
Mereka membawaku ke tongkrongan skena di Pontianak kata mereka, namanya Anseg(Angin Segar). Ketika melihat IG mereka, postingan mereka lebih banyak acara gigs dibanding produk kopian mereka sendiri; dan dengan bangganya menulis tagline di profil mereka “libor kalo ada gigs”, tapi setelah saya cek lagi, sudah mereka ganti.
Setelah memesan beberapa minuman, Gita sudah mengeluarkan minuman khas di sana dalam bingkisan plastik bening. Warna minumannya seperti gula merah, dan rasanya sedikit manis dan mudah ditelan. Meninggalkan hangat di leher, entah karena campuran rempah yang terkandung atau apa saya tidak tau. Mereka menyebutnya Capcuan.
Di Warkop itu saya melihat denyut nadi perkopian di Ponti, mengingatkan saya kepada suasana di Malang. Di sana saya berkenalan dengan beberapa pelaku musik di kota Pontianak, ada beberapa personil Lullavile yang baru saja menuntaskan tour mereka dari Jawa, ada kelompok band ciwi-ciwi HC Punk yang sedang ramai dibicarakan yaitu RUE yang katanya sedang mencari vokalis karena ditinggal anggota lama. Saya sempat ikut personil band rock asal Ponti yaitu LAS!( yang barus saja merilis MV mereka “Kota Kecil dan Rock n Roll” untuk menemaninya membeli capcuan lagi.
Sepertinya Banjarbaru masih asing di telinga mereka, dan mengira satu tempat yang sama dengan Banjarmasin. Berhubung beberapa band dari Banjarmasin seperti Binal terkoneksi dengen lebel musik dari Pontianak. Selain saya pribadi gak terlalu ngeh juga dengan dunia myuziekkk~~~
Esok harinya, saya dan kedua kawan saya harus mengerjakan beberapa garapan di sebuah tambak yang terletak di bantaran sungai Kapuas. di siang hari, daerah khatulistiwa ini benar-benar panasnya kurang ajar. Kami harus merakit beberapa alat pelontar pakan ikan dan memasangnya di keramba apung. kami pikir estimasi pengerjaan yang dimulai dari Jam 10 pagi berakhir sekitar jam 15.00-an, ternyata tidak, molor sampai jam 18.00 lebih sambil sibuk menepuki nyamuk yang mengelilingi tubuh kami yang basah oleh keringat dan bau matahari.
Sesampainya di penginapan, kami segera mandi dan merebahkan diri di kasur sambil uwel-uwelan. Namun Chowny bersikeras untuk mengajakku dan kawan-kawan untuk ngopi di tempat kawannya. Akhirnya kami bergerak menembus padatnya malam minggu di kota Pontianak. Sampai di lokasi kopian yang lebih tepatnya membuka lapak di sebuah lokasi water front yang disulap menjadi taman hiburan dan lokasi murah-meriah untuk melepas akhir pekan bersama keluarga atau pasangan.
Jika melihat suasananya tidak jauh beda dengan Siring yang ada di Banjarmasin, hanya saja di sini sungainya duakali lebih lebar daripada yang ada di banjar. Di situ kami bercengkrama, membicarakan banyak hal sembari memutar arak. Ada beberapa obrolan, seperti bagaimana kami tenggelam dalam euforia dan kejayaan Anarkisme yang naik di awal 2019 dan mulai menurun di pertengahan 2022. Banyak Sentimen emosi ketika sudah begitu lama aku tidak membicarakan gerak politik otonom individu, dan bagaimana memaknai HC Punk sebagai gerakan atau hanya sekedar fashion dan musik saja. Pengaruh alkohol juga sedikit membuatku liar ketika diskusi-diskusi semacam ini dibuka.
Namun obrolan mulai mencair ketika ada seorang kawan bernama Bandi menceritakan sebuah pemukiman di seberang sungai tempat nongkrong, yang dari awal menarik perhatian saya karena warna lampu masjidnya yang mencolok dan terlihat oldschool, yaitu kampung Beting. Tempat yang semua orang di seluruh Kalbar tau kalo itu adalah tempatnya jika kita ingin menikmati sebagian kecil surga dunia. Ada perasaan percaya tidak percaya ketika mendengar cerita mereka, ketika mendengar bahwa kampung itu adalah tempatnya orang-orang alim namun bersandingan juga bisnis narkoba di dalamnya. Obrolan kami sampai ke sejarahnya, dan bagaimana masyarakat di sana juga kerap didiskriminasi oleh orang luar daerah mereka.
Untuk melepas rasa penasaran kami, besok malamnya setelah menorehkan tinta di kulit saya, Gita membawa saya untuk belanja ke sana. Kami melewati jembatan untuk menuju ke sana, jika jalur lama, orang-orang lebih memilih menyewa perahu untuk sampai ke Beting. Sebenarnya Beting masih bagian dari kota lama, dan berada di sekitar keraton kesultanan Pontianak. Dulunya daerah ini adalah tempanya para bajak laut, dan lokasi sangat unik karena berada diujung pertemuan dua sungai, yaitu sungai Kapuas dan sungai Landak. Daerah ini sangat terikat sekali dengan kebudayaan keraton dan komunitas Arab yang ada di sana.
Setelah melewati masjid Jami yang menarik perhatianku semalam, akhirnya kami masuk ke dalam gang-gang yang ada di sana yang berupa jalan berbelah yang dipisahkan oleh kanal-kanal. Jika datang ke sini, pastikan membawa orang lokal agar tidak dikerjain atau dipalak. Kehidupan di sini relatif seperti kampung padat seperti di Banjarmasin, mungkin yang membedakan ada tempat berjudi dan bilik-bilik Warnet yang menyediakan jasa judi online. Kami datang ke sana pada saat perkampungan ini sudah menjadi bagian dari desa wisata, karena sudah banyak pembangunan dan sempat dikunjungi oleh Jokowi juga untuk peresmian water front.
Gita membawa kami ke dalam gang kecil, lalu ada rumah dengan pintu tertutup, namun ada lubang bulat yang diisi oleh paralon di samping pintunya menembus tembok. Di situlah Gita menjulurkan tangannya memberi uang dan menyebut “cung” dan sejumlah nominal; lalu mengambil dan mengambil barang yang kami butuhkan.
Ya, semudah itu.
Setelah itu kami kembali ke tongkrongan yang kami kunjungi semalam. Mereka menyebut tempat kami mabuk-mabuk semalam dengan nama sungai Eko, karena ada kawan mereka yang bernama Eko dan rumahnya tepat berada di belakang water front. Bayangkan bagaimana kesalnya kamu ketika membuka pintu dan yang pertama kau lihat adalah tembok. Itu yang membuat dia kesal dan mencabut bendera partai yang dipasang sepanjang water front. Ada juga kelakuan unik yang dia lakukan, yaitu memotek kamera CCTV yang terpasang di sepanjang wilayahnya, agar kegiatan minum dan ngecung tidak terganggu.
Mungkin itu saja cerita saya selama beberapa hari di sana. Mungkin sisanya hanya kepayahan karena jauhnya perjalanan. Sampai di Banjarbaru saya langsung diserang demam dan flu. Tapi saya tidak kapok untuk main ke sana lagi; mungkin jika bisa tidak hanya di kotanya–tapi lebih masuk lagi ke pelosok ke wilayah-wilayah komunal Dayak yang masih bertahan di rumah betang. Mungkin suatu saat, selama masih diberi nafas dan waktu.