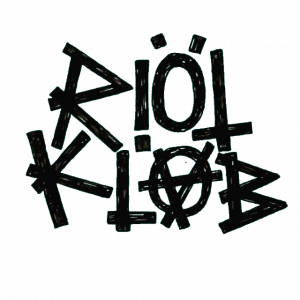Di tulis oleh bsky
Sinar mentari masuk lewat celah-celah papan kecil ini. Entah sudah berapa lama aku tertidur, tapi yang pasti hari sudah siang.
Sungguh tak tau diri, semua orang sudah tidak ada. Jendela masih tertutup, pasti ibu sengaja tidak membukanya, agar wajahku tidak berkontak langsung dengan pekatnya sinar matahari; atau mungkin saja ia malu jika ada orang melongo dari luar dan melihatku masih terlelap. Dasar pikiran jelek.
Keluar kamar kupandangi seisi rumah, pendul menunjukkan tepat jam 12.00. Bingo, apakah itu sebuah kebetulan, aku pun tak tau. Yang pasti sebentar lagi adikku pulang dari sekolahnya–membawa tampang kuyu karena kelelahan usai berjalan kaki di bawah teriknya matari.
Setelah itu dilanjut ibuku yang pulang dari kebun. Membawa peluh dan kejenuhan usai menyayat pohon karet yang berjejer tak habis-habis.
Sebelum aku menyadari ketidak bergunaan ini, terlihat tumpukan piring kotor yang tak terjamah, ada baiknya segera kucuci. Aku tak ingin melakukan satu kegiatan saja, segera kusambar sebuah sapu, lagian rumah ini tidak terlalu besar, jadi tidak terlalu menguras tenaga. Namun ini semua masih belum cukup, ada beberapa pohon karet yang belum digores. Segera kuambil pehet untuk menoreh beberapa pohon yang ada di sekitar rumah ini, lagian toh tak terlalu banyak juga jumlahnya.
Aku menyadari bahwa aku adalah seorang pemalas, dan aku mengamini itu. Aku tak ingin berguna kalau itu hanya membebani diriku sendiri. Tidak ada salahnya juga to.
Lumayan juga usai menandaskan beberapa pohon karet ini. Tidak bisa kubayangkan jika kubandingkan dengan beberapa tetangga yang memiliki beberapa kebun dan ratusan pohon karet, bagaimana jenuhnya mereka menghadapi pohon karet yang berjejer lurus seakan-akan tidak ada habisnya. Mungkin tampak menggiurkan untuk hasilnya jika sudah dipulung dan ditimbang pada tengkulak, namun jika harga getah turun dan ada maling karet berkeliaran menyabet segala hasil jerih payah mengisi beliwang sampai terisi penuh, bisa gigit jari mereka. Terbayang bagaimana membayar utang atau angsuran sepeda motor yang sedang menanti.
Sangat sering aku mendengar dari orang tua, saudara, tetangga, bahkan sebuah lagu bahwa “tidak ada masa depan yang cerah untuk seorang penyadap karet”. Penghasilannya hanya cukup untuk makan dan membayar utang, tidak ada kesempatan untuk menabung. Jika ada keperluan mendadak seperti membayar biaya sekolah, sakit, bahkan kematian terpaksa memutar otak entah itu mengutang lagi atau yang paling menyesakkan adalah menjual kebun. Setelah tidak ada lagi kebun yang tersisa, terpaksa memburuh untuk menggarap kebun orang dengan sistem bagi hasil, itu pun penghasilannya tidak seberapa.
Itulah mengapa pada saat kelas 3 sekolah dasar ibuku memarahiku karena mendapat laporan; pada saat ibu Ani mengajar menanyakan tentang cita-cita, beberapa kawanku menjawab dengan mantap ingin menjadi guru, polisi, tentara, dan beberapa cita-cita pasaran lainnya. Namun pada saat giliranku, dengan entengnya aku menjawab bercita-cita ingin menjadi seorang pemantat karet(bahasa Maanyan untuk menyebut menoreh/menyadap karet).
“Kog bisanya kamu mau jadi penyadap karet,” Ujar ibuku muntab, “masak dari buyutmu, kakekmu, sampai ibumu jadi penyadap karet semua. Gak ada yang mau memperbaiki nasib.” Dan beberapa kata yang memberondong menghakimiku.
Walau aku tau itu adalah bahasa klise yang diucapkan ribuan orang tua di daerahku kepada anaknya agar giat belajar dan bersekolah yang tinggi dan kelak akan menjadi orang yang sukses walaupun itu dengan cara menipu, yang terpenting bisa memperbaiki atau membangun citra orang tua.
* * *
Hari kian terik saja, sang surya seperti tepat di atas kepala. Sebenarnya tidak benar menyadap pada siang hari, karena getah karet pasti tidak lancar mengalir dan cepat kering, hanya melakukan pekerjaan yang sia-sia saja.
Ah, persetanlah, yang terpenting aku melakukannya agar tidak terlalu terlihat sebagai orang yang tak berguna. Sebenarnya aku juga muak dengan bau karet yang tak sedap ini dan terkenal susah hilang aromanya walau sudah dicuci sebersih mungkin. Biasanya orang di tempatku menggunakan minyak tanah untuk menghilangkan aroma tak sedap dari karet. Namun dengan beralihnya kompor kayu ke gas penggunaan minyak tanah semakin kurang dan mengalami kelangkaan, mungkin banyak yang beralih ke bensin. Ah, persetan lagi dengan bau karet, hidup para penoreh karet itu sudah susah, tidak ada waktu untuk memikirkan baunya–kalau sudah menimbang dan uang segera dicairkan.
***
Badanku sudah bermandikan peluh, sepertinya melakukan ritual mandi terlihat nampak menyenangkan. Di sini tidak ada yang lebih menyenangkan selain mandi dan menceburkan diri di sungai. Segera kusambar gayung dan handuk. Kesenangan kecil ini jangan disia-siakan.
Usai menyegarkan badan di sungai segera kuberanjak kembali di rumah. Kulihat ibuku dan adikku sedang makan siang dengan seragam masih melekat di badan.
“mamat, makan.” Ujar ibuku.
“Iya” menhampiri.
Ibuku segera menyiapkan nasi di piring, sembari menunggu aku yang sedang berpakaian.
“Aduh belum sarapan aku tadi.” Keluhku.
“Ariii, kenapa gak sarapan?”
“Nggak tau, belum lapar aja tadi”
“Ulah, salah kamu sendiri” sambil menyodorkan piring berisi nasi yang masih mengepul.
Sedang nikmat-nikmatnya menikmati hidangan oseng-oseng sulur favoritku, akhirnya pertanyaan itu tiba juga.
“Jadi bagaimana rencanamu setelah memutuskan untuk keluar dari kuliah ini, ibu sudah tidak kuat lagi menahan cibiran orang luar?” Sambil terisak, tidak kuat menahan tangis.
Aku masih diam saja. Masih kuingat keputusan sepihakku untuk memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah. Persetan dengan kampus pencipta para predator sexs ini. Mereka tidak mengakui kesalahan mereka, kenyataanya mereka justru menutup-nutupi kesalahan dengan dalih nama baik almamater dan yayasan. Dan sampai saat ini sang penjahat masih berlenggang bebas tanpa tanpa ada yang menghalangi, dan bisa saja dia masih mencari korban selanjutnya.
Setelah mengetahui kebejatan seorang dosen yang telah melakukan pelecehan seksual pada seorang mahasiswi, aku dan beberapa kawan memutuskan untuk mem-blow up kasus ini lewat media pers mahasiswa. Sebagai seorang pemimpin redaksi saya sudah menebak, mengangkat isu sensitif seperti ini pasti akan menuai kecaman, walaupun aliran simpati juga berdatangan dan mengutuk sang pelaku, tapi pihak kampuslah yang punya kuasa dalam memutuskan.
Gerakan advokasi dan menggalang solidaritas lewat media sosial dan petisi terus mengalir. Namun itu hanya seperti angin lewat belaka. Kasus kian tenggelam, dan semua orang perlahan-lahan mulai lupa. Lupa. Lupa adalah penyakit.
Setelah itu hari-hari dipenuhi teror oleh pihak kampus, tidak hanya lembaga pers yang kunaungi terancam dibekukan, tetapi sebagai salah satu penanggung jawab dalam redaksi aku pun mengalami kendala dalam proses pembuatan skripsi. Ada satu syarat agar aku bisa melanjutkan skripsi lagi, yaitu meminta maaf pada orang yang kutuduh sebagai pelaku pelecehan, dan mengahapus semua konten tulisan yang berisi kritik pada kampus.
Sepertinya aku makin muak saja dengan apa yang terjadi. Mereka hanya bersembunyi di balik kedok nama besar institusi pendidikan agama, namun nyatanya di balik itu mereka hanyalah para penyamun yang siap menghabisimu kapan saja.
Segera kubanting pintu kantor dosen itu, tanpa salam; tanpa memandang ke belakang. Kutinggalkan mereka selamanya.
Segera kukemas barang-barangku di kos yang hanya sedikit itu. Ada beberapa buku yang mustahil untuk kubawa. Segera ku-packing, kira-kira ada empat kardus. Aku bingung akan kuapakan. Sedikit menimang-nimang akhirnya kuputuskan, satu kardus kusumbangkan ke salah satu Perpus jalanan yang sangat membutuhkan koleksi buku.
Lalu kukeluarkan lagi buku-buku itu berdasarkan buku penting dan buku biasa(menurutku) dengan perasaan berat hati dalam memilihnya.
Akhirnya kuputuskan satu kardus akan kubawa, sedang dua kardus lainnya akan kujual ke salah satu kawanku seorang penjual buku bekas. Dengan sedikit paksaan dan iming-iming ada beberapa koleksi buku yang langka, akhirnya aku mendapatkan uang yang kurasa lebih dari cukup untuk bisa pulang.
***
Setelah kapal ditambatkan di dermaga pada saat langit sedang merah-merahnya menyisakan setengah matahari di cakrawala. Aku sampai juga di pulau ini, diiringi sambutan di depan pintu keluar oleh para tukang ojek jasa travel yang tentunya aku tolak dengan sopan.
Sialnya, kawanku tak kunjung datang. Padahal aku sudah menghubunginya sedari tadi pada saat kapal masih mendekati pelabuhan. Berbatang-batang rokok sudah kuhabiskan, kopi yang kupesan di salah satu kedai kecil yang kusinggahi juga sudah tandas.
Tiba-tiba muncul motor dari arah barat, barat? Sejak kapan aku tau arah mata angin?
“Sorry mas, tadi lagi macet parah, inikan lagi jam orang pulang kerja, lagian aku lagi gak ada paket. Jadi aku keliling-keliling dari tadi cari sampean.” Ujarnyanya meyakinkan.
“Ahh, terserah kamulah, dari dulu kamu memang gak beres. Yang penting aku menginap di kosmu untuk malam ini”. Ujarku sedikit jengkel.
Nama seseorang yang menjemputku adalah Duwik, anak dari sahabat bapakku pada saat mereka merantau ke Kalimantan. Sekarang dia menempuh pendidikan di salah satu kampus kenamaan di Banjarmasin. Beruntung juga dia dengan tingkat kepintaran yang tidak terlalu. Ya, orang beruntung bisa di mana saja.
“Kenapa balik Kalimantan mas?” Tanyanya.
“Aku suda D.O dari kampus,” sebelumnya dia tidak kuberitau kalau sudah berhenti dari kampus laknat itu.
“Wah, gak sayang itu, padahal tinggal wisuda aja”.
“Biarkanlah, aku sedang tidak ingin membicarakan itu.”
“Wah, iya maaf gak jadi tanya kalo gitu.”
Ternyata Duwik ini lumayan cerdas juga bagaimana cara untuk mengulik alasanku untuk kembali ke Kalimantan. Segera dia berhenti di salah satu toko kelontong dan dengan cengengesan sudah membawa tiga botol anggur. Setelah berkelok-kelok menerobos gang yang masih beralas papan kayu untuk menghindari kemacetan, kami akhirnya sampai di sebuah kampus.
“Loh, kog kita malah ke UKM sih?” Ucapku bingung.
“Gpp mas, kita malam ini tidur di sini aja. Sekalian sampean ngisi materi jurnalistik”. Sambil terkekeh.
“Brengsek kamu ya, nyulik aku.” Tidak habis pikir.
Walau sebenarnya aku sudah tau, culik menculik di pers mahasiswa sebagai pemateri adalah sebuah budaya yang sudah langka. Beberapa lembaga pers mahasiswa sekarang lebih suka mengundang selebgram yang nyambi sebagai penulis demi meraih oplah pengunjung yang datang pada saat acara sastra. Atau aku hanya sinis?
“Kog bisa kamu masuk pers?” tanyaku penasaran.
“Ya gara-gara sampean lah. Siapa lagi?..” kembali terkekeh.
“taek kamu, jangan terpatron. kill your idol” ucapku emosi.
“Sudahi quote-nya, mending sampean cerita kenapa keluar dari kampus?”
“Jadi gini ceritanya (……)”
“Udah ngomong orang tua?”
“Belumsih, makanya aku bingung”.
“Gapapa, dipikir sambil ngombe aja” terkekeh lagi.
“Wooo jancuk”.
***
Ternyata setelah pertemuanku dengan Duwik bukan jadi pertemuan terakhir perjalananku untuk pulang. Setelah kutimang-timang, akhirnya aku memutuskan untuk mengelilingi Kalimantan, mungkin ini adalah perjalanan yang terinspirasi dari seorang tokoh dayak bernama Tjilik Riwut yang melakukan perjalanan mengelilingi Kalimantan yang pada saat itu kondisi aksesnya perjalanan masih sangat sulit, berbeda dengan kondisi sekarang; walau masih ada beberapa daerah yang masih belum terjamah oleh kendaraan alat berat.
Dengan beberapa uang yang masih tersisa, kuputuskan untuk memulainya dari arah barat dari Banjarmasin menuju Palangkaraya. Setelah itu berlanjut ke Kinipan di ujung barat Kalimantan Tengah. Dengan lika-liku interaksi yang kualami, berinteraksi dengan beberapa individu dan latar belakang hidup yang berbeda membuatku semakin meledak; sebagai orang yang mendaku sebagai egois ini sungguh menyakitkan.
Perjalanan berlanjut dari hulu Kapuas sampai ke hilirnya di Putussibau. Di sana aku bertemu kawan bernama Bimo yang sedang melakukan riset antropologi perihal orang dayak yang masih menjalankan kehidupan komunal dan tinggal di sebuah rumah betang. Di sana mungkin aku bisa membantu beberapa hal seperti membantu mencari data atau sekedar ikut warga berburu menggunakan alat tradisional sumpit.
Hal gila lainnya aku menembus belantara pegunungan tengah Kalimanntan bernama Muller untuk menemukan hilir mahakam dan sampai di kota Samarinda. Dan beberapa perjalanan lainnya yang tidak bisa penulis masukkan ke dalam cerita ini.
Setelah melakukan perjalanan yang sebenarnya tidak ada habisnya itu. Akhirnya sampailah aku di rumah dengan keadaan kumal dan kurus kering setelah hilang tanpa ada kabar beberapa tahun. Perjalanan yang menyakitkan. Kepanasan; kehujanan; kelaparan; namun semua itu tidak yang lebih menyakitkan dibandingkan dengan tangisan ibuku.
Aku hanya bisa bersujut dan minta maaf. Tidak lebih.
***
Pendul jam kembali berdetak dari lamunanku.
“Jadi bagaimana maumu?.” Tanya ibuku sambil terisak.
“Aku sudah memutuskan diri untuk menjadi penyadap karet, mungkin aku juga akan mulai memanfaat lahan untuk ditanami agar kita tidak bertahan hidup dari karet saja. Mungkin ini terlihat naif, tapi aku yakin sesusah apapun hidup kita–aku berjanji setidaknya–tidak kelaparan setiap harinya.” Ujarku mantap.
Dalam hati kecilku. Aku berjanji membahagiakanmu ibu. Aku pernah membaca sebuah buku, pada judul buku itu tertulis “Hidup itu indah, dan hanya itu yang kita punya”.
orologireplica.is è il miglior negozio di orologi replica al mondo. Offriamo solo orologi svizzeri replica cloni 1: 1 della massima qualità.
The best replica Rolex watches site in the world only sells the top quality AAA swiss replica watches.
Les meilleures répliques de montres bon marché du Royaume-Uni AAA à des prix abordables peuvent être trouvées sur ce site Web.