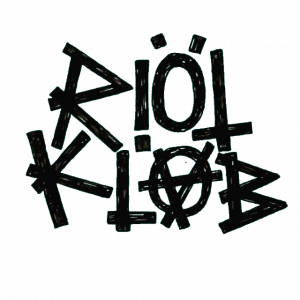Aku berusaha tenang, mencoba mengontrol suatu hal yang ganjil yang tiba-tiba meluap-luap entah dari mana. Tidurku jadi tak nyenyak. Kubayangkan esok lusa harus bagaimana. Apa yang akan kubicarakan untuk memulai obrolan. Apa aku harus mencair atau berpura-pura tetap dingin. Di tengah risauku, tiba-tiba obituari masa lalu muncul kembali: tentang kenangan-kenangan itu, tentang kepahitan, pesakitan itu.
Sampailah waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Aku sudah siap dengan penampilan terbaik. Tak banyak dandan berlebih. Hanya kaos hitam seperti biasanya, kemeja flannel, celana jeans, dan sepatu converse tempur yang sudah buluk yang mulai meranggas daya rekat lemnya.
Sebetulnya jarak tempuhku ke titik pertemuan ini lumayan jauh. Butuh sekitar setengah jam perjalanan. Sementara kami tinggal di kota yang berbeda, hanya beda administratif saja. Ketika sampai di lokasi, terduduklah aku seperti sekarang di sebuah halte ditemani hawa panas dan debu jalanan.
Kenapa tidak di cafe, atau restoran mahal saja sekalian. Kenapa harus di halte, keluhku. Toh ekonomiku kini lebih baik. Tak lagi seperti tahun-tahun lalu, saat aku terpaksa membabu pada kapitalis yang dulu pernah kucaci maki ketika masih berkuliah. Impulsif.
“Apa dia akan membunuhku lagi?” Pikiranku cemas.
***
Siang itu terasa terik, aku duduk di bangku halte ditemani sebatang rokok di jepitan jari tangan kananku, dan menggenggam kantong es cekek di tangan kiri.
Lama-lama aku jengah juga menunggu, menunggu memang menyebalkan, penyakit. Mataku menyoroti tiap kendaraan yang berlalu-lalang. Kurogoh seluler dari dalam kantong, kuperiksa apakah ada pesan masuk. Huh, hasilnya nihil.
Ketika mengalami kesuntukan akut semacam ini, mataku mulai bergerilya mengamati apa yang ada di sekitarku. Ada paman pentol di seberang yang tadi sempat kubeli jajaannya. Dia duduk tersandar di sebuah pohon dengan kepala menunduk yang nampaknya mulai diserang kantuk berat. Dengan sengaja dia agak menurunkan topi coklatnya agak kebawah agar cahaya tidak terlalu terpapar ke arah wajahnya.
Kuloloskan lagi sebatang rokok dari bungkusnya. Sebelumnya kubasahi bibirku dengan air liur, agar filternya tak menempel di bibirku saat aku sedang menariknya. Kupikir membeli rokok kretek filter tidak cocok untuk kondisi panas semacam ini, tenggorokanku mudah kering, sedikit-sedikit aku harus menyesap es cekek setelah beberapa hisapan rokok.
Pandanganku teralihkan pada wanita yang berhenti di gerobak pentol paman di seberang. Dia mematikan sepeda motor matic-nya, lalu menyandarkan dan membangunkan paman pentol dengan pelan; yang sepertinya sudah tenggelam dalam mimpi.
Gadis itu menyodorkan beberapa lembar uang ribuan, lalu menunjuk beberapa varian pentol dan ukurannya. Dalam kondisi setengah sadar, dengan wajah kuyu paman itu perlahan memasukkan pentol ke dalam plastik, sembari mengingat-ingat sudah berapa tusuk pentol yang ia masukkan.
Aku diam-diam memperhatikan perempuan itu. Sial. Dia menutupi parasnya dengan masker. Tipikal karyawan karir pada umumnya. Membosankan dan terlihat template. Aku sering menemui mereka di rombong-rombong para penjaja kaki lima, atau festival musik yang mendatangkan musisi ibukota.
Kubuka kunci layar gawai, untuk yang ini aku mengumpat. Lagi-lagi tak ada pesan masuk, lebih tepatnya darinya. Hanya beberapa pesan dari grup kerja dan kawan nongkrongku. “Siang ini ngopi di mana guys?” Isi pesan di grup tongkronganku. Untuk grup kerja aku enggan membukanya, aku tak ingin pertemuan ini terganggu oleh hal sekecil apapun.
***
“Mas,” ia membuka obrolan.
Sebelumnya aku berjanjian dengan seorang gadis, perempuan yang pernah kukenal beberapa tahun lalu. Lewat pesan pendek di Instagram, dia menghubungiku.
“Iya, ada apa M?” Aku seperti biasa, selalu antusias, selalu menanti, dan diam-diam mengikuti aktivitasnya di media sosial.
“Apa kabar?”
“Seperti biasa, berjalan apa adanya.”
Ingin sekali kugelontorkan berbagai macam pertanyaan, “aku rindu, aku masih di sini mengharapkanmu, aku … Aku…” Ah, ucapan itu tercekat. Otakku lumpuh, jariku keram, dan aku harus terlihat elegan tidak gegabah.
“Puji tuhan, baguslah kalau begitu,” syukurnya dari kejauhan.
“Bagaimana dengan kabarmu?”
“Puji tuhan, aku baik-baik aja di sini, udah pindah kerjaan juga. Mulai sibuk dan ngumpulin duit wkwk.”
“Ya, baguslah kalau begitu.”
Aku harus terlihat dingin. Tak boleh terjebak dengan kalimat panjang. Bisa saja itu kalimat jebakan yang sering digunakan para wanita. Mereka selalu punya daya magis untuk membuat kita larut dan menumpahkan segala keluh kesah yang seharusnya tak perlu diutarakan.
Aku pertama kali mengenalnya di sebuah acara gigs musik. Ya, itu pertama kalinya aku mengunjungi acara musik underground di kota ini. Sambil berdesakan mencari spot yang cocok demi melihat para penampil. Aku berada di samping sound, peduli setan terlihat asing di kerumunan.
Seperti biasa, aku hanya mengangguk-angguk kepala, menikmati sajian yang ditampilkan. Suara bising musik, raungan vokalis yang sesekali bergimik ala GG Allin, dan para audiens yang memenuhi arena moshpit dengan beribu pogo lalu diam-diam merebut mic dari vokalis demi menyumbang suara sumbang mereka.
Suasana terasa bergairah. Aku menyebutnya hiburan kaum pekerja, yang melampiaskan kejengahan dari pabrik pemilik modal. Di sini, mereka bisa mengekspresikan segala hal tanpa memikirkan deadline kerja bahkan angsuran hutang yang selalu menghantui tiap bulannya.
Tanpa sengaja mataku terpaku pada seorang gadis yang sibuk dengan gawai di genggaman tangannya. Dia merangsek masuk demi mendapatkan angle terbaik mengabadikan video dan gambar. Untuk saat ini, seluruh konsentrasiku teralihkan padanya.
Rambut hitam sebahu itu, pipinya yang chubby, kulit yang bersih, lalu senyumannya. Duh, terlalu spesial. Tubuhnya tak begitu tinggi, mungkin sekitar 150-an senti. Namun bukan jadi soal.
Sialnya kami saling bertemu pandang. Reflek, aku pura-pura menikmati band yang perform, berusaha mengalihkan perhatianku darinya.
Selang beberapa menit, kulihat lagi ke arahnya. Alamak, dia sudah pindah posisi. Kucari ke sekeliling, namun tak ada titik terang. Jarak pandangku juga terganggu kemelut kerumunan di area moshpit. Band penampil yang satu ini terlalu energik, nampaknya ia punya cukup nama di scene lokal kota ini.
“Orang baru mas?” Suara orang dari samping. Kupalingkan wajahku. Demi apa, gadis itu sudah berada di sebelah.
“Iya, dan baru pertama kali ke sini.”
“Gimana mas?” Suaranya agak meninggi. Suara sound terlalu pengang dan ini mengganggu interaksi kami.
“Ya, orang baru,” kubalas sedikit lebih lantang.
“Ohhhh,” ucapnya singkat.
” Salam kenal, namaku B.”
“M, salam kenal juga, selamat datang di kota ini. Ya beginilah kondisi skena di kota kami,” ia menyambutku.
“Mau air putih?” Tawarku padanya, sambil menyodorkan botol tumbler.
“Arak?”
“Air mineral biasa, straight edge hahaha,” berusaha tetap dingin sambil menyilangkan tanganku.
“Ohhhh~~~” tutupnya.
Mungkin itu kenalan singkatku dengannya. Seusai acara, kami sempat duduk sejenak untuk menghela nafas di luar gudang terbengkalai yang diokupasi menjelma venue acara gigs oleh sebuah kolektif di kota ini.
Dia sempat menggerutu karena sempat percaya aku adalah straight edge. Sambil menghisap rokok sembari bercengkrama, dia mulai bercerita tentang dirinya. Ia berkata telah lama jadi bagian dari kolektif ini, bertugas di bagian media dan dokumentasi. Selain itu, dia juga aktif menulis di sebuah majalah zine. Kebanyakan tulisannya membahas tentang eksistensi perempuan di scene underground.
“Memang benar, awalnya scene Hardcore Punk ini dibangun oleh para pria, tapi seiring perkembangan zaman–yang namanya musik juga akhirnya mengglobal dan bisa dinikmati oleh siapapun– tidak terkecuali perempuan. Aku menolak sih kalo cewek datang ke gigs cuma jadi bahan objektifikasi para pria aja,” ucapnya dengan kultum berapi-api.
Aku hanya mengangguk saja, berusaha untuk mendengarkan dan menghormati apa yang menjadi landasannya dalam menjalani hidup yang makin terbatas pilihannya.
Dia lalu memperkenalkanku pada beberapa rekan-rekannya di kolektif itu. Kami berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang ekosistem musik dan pergerakan di kota yang dulu pernah kutinggali dengan kota mereka.
***
“Kamu lusa besok sibuk gak?” Ucap pesan di sana.
“Belum tau, hidupku selalu tidak terjadwal.”
“Mau ketemu gak?” Ajaknya.
Sedikit kulambankan jawaban, sebisa mungkin aku terlihat sedang berpikir. Padahal tentu saja aku mau. Hari ini pun, jika dia mengajak, langsung ku-starter Astrea bututku.
“Bisa, di mana?”
“Temui saja aku di halte Jl. A.Yani, jam dua belas siang. Nanti kita ketemu di sana.”
“Baik,” jawabku singkat, berlagak dingin.
“Terima kasih, mas.”
Setengah jam lamanya menanti, tiba sebuah motor berhenti tepat di hadapanku. Dia langsung membuka helm. Aroma parfum menyerebak dari tubuhnya. Aroma yang seperti dulu.
“Maaf, harusnya aku balik dulu, tapi ada briefing dadakan.”
“Ya, tidak apa,” tentu kumaafkan keterlambatannya.
“ Apa kamu mau mengantarku sebentar kembali ke kantor? Aku memboncengmu saja,” sialan, ia merayuku dengan senyum manisnya.
“Oh, bisa.”
Setelah mengantarnya, kami pun berjalan membelah kepongahan kota. Mampir sebuah warung soto Banjar untuk makan siang. Tidak banyak yang kami bicarakan. Tidak ada yang memulai, mungkin karena masih sedikit canggung. Kami lebih sibuk dengan apa yang disajikan dalam mangkok dan segarnya teh Gunung Satria.
Urusan perut sudah teratasi dan kami mulai beranjak ke perpustakaan kota.
Aku tengah asik melihatnya memilin-milin buku yang tertata di atas rak. Sampai dia sadar kalau sedari tadi aku tak terlalu banyak bereaksi, hanya melamun sibuk memandanginya.
“Kenapa ngeliatin kayak gitu?” Semua kata yang keluar dari mulutnya tak ubahnya mantra sihir.
“Kamu cantik hari ini,” godaku.
“Hahaha dasar, kamu selalu menggunakan kata itu. Sudah berapa wanita yang kamu gombali dengan kalimat itu?”
“Hanya untukmu,” tentu saja aku berdusta. Setelah hubungan terakhirku dengannya, aku mencoba berkenalan dengan beberapa perempuan. Namun aku seperti diberi kutukan. Tidak ada yang benar-benar mampu mengetuk hatiku.
“Kamu dulu pernah bilang ingin library date?”
“Ya, ini sungguh menyenangkan, tapi lebih menyenangkan lagi jika itu adalah terus bisa bersamamu.”
“Tuh, gombal lagi. Kamu selalu terlihat sedih di media sosial, tapi sepertinya sudah banyak wanita yang kamu ajak ke tempat unik semacam ini selain di cafe atau kedaimu dulu,” ia seperti memperhatikan gerak gerikku.
“Tidak, itu muncul dari keresahan hati,” jawabku sambil nyengir.
Usai puas mengelilingi seluruh isi perpustakaan yang buku-bukunya lebih banyak berdebu daripada tersentuh oleh tangan manusia, kami beranjak ke lokasi tujuan selanjutnya.
***
Angin dermaga berhembus cukup kuat, rambutmu yang kemilau terkibas-kibas diterpa olehnya. Gelombang di muara sungai Barito ini juga lumayan besar. Sambil melihat perahu motor berkelok-kelok menghindari kapal tongkang pemuat batubara yang terlihat angkuh melintasi perairan ini.
Di dermaga ini lumayan sepi kapal bersandar. Hanya beberapa saja, paling-paling ada taksi air yang setiap jamnya mengangkut penumpang menuju sebarang atau sebaliknya. Mungkin satu yang unik dari semua pemandangan ini, sebuah kapal berbahan dasar kayu yang setia bersandar di sudut pelabuhan.
Namanya Pancar Mas, sudah bertahun-tahun kapal tua itu melayani perjalanan dari kota ini menuju kota di hilir sungai. Menawarkan jasa untuk mereka yang tinggal di sepanjang bantaran sungai Barito ini yang beberapa masih susah atau sama sekali tidak bisa diakses lewat darat.
“Kamu ke mana saja sekarang?” Pertanyaannya membangunkanku dari lamunan.
“Aku masih di sini.”
“Bukan, maksudku aku sudah tidak pernah lihat lagi kamu aktif di acara musik dan kolektif yang kamu buat itu.”
“Ohhh, aku pernah bilang, jika di umur 27 aku berhenti dari berbagai macam kegiatan yang ada di dunia apapun, dan menyerahkannya pada mereka yang ada di bawah saya. Jika mereka keberatan untuk melanjutkan, mereka kuminta untuk bergabung ke wadah yang lain; lalu kolektif itu dibubarkan saja.”
“Kamu tau tidak, itu seperti hilang ditelan angin.”
“Ya, dan angin itu pula yang mempertemukan kita di sini.”
“Kamu datang dengan cepat, melakukan banyak hal, lalu kamu pergi begitu saja setelahnya?”
“Aku punya banyak hal yang perlu dilakukan selain kerja-kerja semacam itu.”
“Apakah aku menyakitimu?” Dengan nada serius, ia mulai memperbaiki posisi duduknya.
“Tidak, aku sudah terlatih kecewa, dan hidup di dunia ini kita harus terbiasa dengan kecewa,” aku denial.
“Tidak usah berlagak kuat. Aku masih ingat kau merengek dan segala hal lainnya yang kamu sembunyikan di kawan-kawanmu,” dia masih berusaha memojokkanku.
“Mungkin waktu itu aku terlalu dibutakan oleh cinta.”
“Hahaha, kamu selalu lucu mas.”
“Tidak ada yang lucu dari sebuah tragedi. Lalu apa tujuanmu mengajak bertemu denganku?” Kumulailah serangan balik.
“Takdir mungkin,” jawabnya polos.
“Jawaban yang terlalu biasa.”
“Lalu yang tidak biasa apa?”
“Aku merindukanmu?”
“Hahahaha itu boleh, jika itu yang kamu mau.”
“Terima kasih,” berusaha terlihat biasa.
“Setelah menikah dengannya, pria itu mudah ringan tangan padaku. Awalnya dia membuatku seperti ratu, namun lambat laun dia mulai berubah. Apalagi semenjak kami tidak kunjung diberi momongan.”
Menurunkan nada, lalu menyandarkan kepalanya di pundakku. Sebenarnya aku agak kikuk sebab diperhatikan warga yang memancing di sepanjang dermaga.
“Lalu, apa yang harus kulakukan?”
“Tidak ada yang perlu kamu lakukan, cukup dengarkan ceritaku aja,” ucapnya sambil sesekali mengusap air mata. Sedang aku hanya duduk terdiam mematung.
“Kenapa kamu tidak cerita pada kawan-kawanmu yang lain saja, aku tak lebih dari orang yang lama dan asing?”
“Baiklah, aku minta kau mengikhlaskanku. Lupakan semua hal yang pernah kita jalani, lupakan semua kesalahan yang pernah kulakukan,” ia memelas.
“Sepertinya aku sudah selesai dengan itu.”
“Bohong,” ucapnya, “jika kamu sudah selesai dengan itu, harusnya kamu tidak datang ke sini, atau masih bersikap manis seperti tadi.”
Ia kembali ke posisi awal, menatap wajahku dengan mata berbinar. Aku masih mematung, memandangi cakrawala yang mulai memerah. Sedang terpaan angin mulai semakin terasa kencangnya.
Jika itu hal yang mudah, sudah dari dulu kulakukan. Aku hanya menjalani hidup saja untuk sekarang, tidak lebih. Kamu yang memilih untuk pergi meninggalkanku. Aku sudah lama menahan penderitaan ini. Cukup jalani saja sisa hidup ini.
Kami berdua lalu membisu, tenggelam dalam kubangan nasib yang muak. Tiada lagi kata terucap. Tangismu pecah, kuusap air matamu lalu kusodorkan sebotol tumbler. Tak seperti yang kulakukan di awal kami berjumpa, karena kali ini ia berisi racun. Setidaknya kali ini bukan aku yang terbunuh. Setidaknya kami berdua.
Editor: Zayn